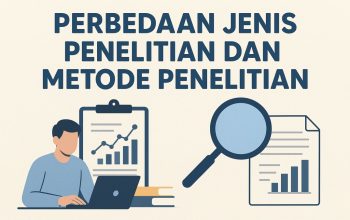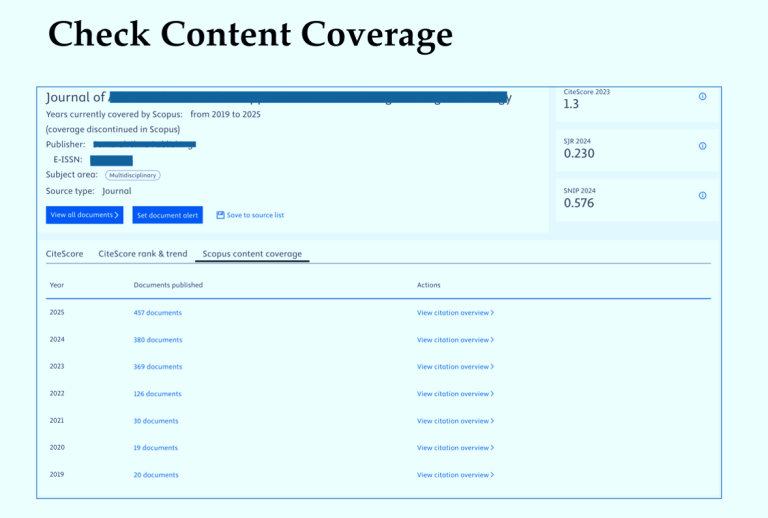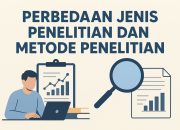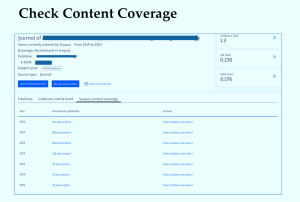Beberapa waktu lalu, tepatnya tangal 6 Mei 2025, saya berkesempatan menjadi pemantik dalam sebuah diskusi penting yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Teknik Mesin-Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSTM-PTM). Topik yang kami bahas adalah Kampus Berdampak, sebuah gagasan baru yang digaungkan Kemendikbudristek sebagai penyempurnaan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Awalnya saya mengira ini hanya pengulangan jargon yang dibungkus dengan nama baru. Tapi setelah saya renungi, konsep ini membawa napas yang berbeda.
Kampus Berdampak bukan hanya tentang memperluas ruang belajar mahasiswa, melainkan tentang menghadirkan kampus secara nyata di tengah masyarakat. Pendidikan tinggi tidak lagi bisa cukup puas hanya dengan menjalankan proses akademik internal. Kita harus mulai bertanya lebih dalam: Apa yang sudah diberikan kampus kepada masyarakat? Bukan sekadar berapa banyak lulusan yang dihasilkan, tetapi sejauh mana lulusan itu benar-benar menjawab kebutuhan zaman.
Empat Jenis Dampak yang Harus Dicapai Kampus
Dalam kerangka Kampus Berdampak, ada empat dimensi utama yang menjadi tolok ukur: sosial, ekonomi, lingkungan, dan personal (mahasiswa itu sendiri). Artinya, kita tidak bisa lagi menilai keberhasilan mahasiswa hanya dari IPK atau nilai skripsi. Harus ada output nyata, entah itu inovasi teknologi sederhana, produk digital, model bisnis sosial, atau keterlibatan dalam proyek pembangunan berkelanjutan. Level dampaknya juga dapat diarahkan, mulai dari tingkat lokal, nasional atau internasional. Dengan cara ini, setiap program pendidikan bisa ditargetkan secara lebih strategis sesuai dengan lingkup masalah yang ingin diselesaikan.
Mahasiswa Tidak Lagi Mengejar IPK, Lulus, dan Mencari Kerja
Dalam diskusi itu saya mengangkat satu fenomena penting yang tidak bisa lagi kita abaikan:
Indonesia saat ini mengalami kelebihan pasokan pencari kerja dan kekurangan pencipta lapangan kerja
Ini bukan sekadar statistik atau tren pasar tenaga kerja, namun sinyal bahwa sistem pendidikan kita belum sepenuhnya berpihak pada pembangunan karakter kreatif dan solutif.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong oleh investasi perusahaan nasional maupun internasional ternyata belum cukup kuat untuk menyerap angkatan kerja muda yang setiap tahun terus bertambah. Bahkan, dalam beberapa sektor, efisiensi industri justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja baru. Akibatnya, banyak lulusan universitas yang terjebak dalam kompetisi mencari pekerjaan, alih-alih memikirkan bagaimana mereka bisa menciptakan pekerjaan.
Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar mahasiswa Teknik Mesin di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tidak lahir dari keluarga entrepreneur. Kebanyakan mereka tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang lebih mendorong pola pikir “bekerja setelah lulus,” bukan “membangun usaha setelah lulus.” Padahal, dengan bekal pengetahuan teknis dan keterampilan rekayasa yang mereka miliki, mereka sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi entrepreneur berbasis teknologi, asalkan diberikan ruang, pembinaan, dan pengalaman yang tepat selama kuliah.
Di sinilah peran kampus menjadi sangat krusial. Kampus tidak cukup hanya mendidik untuk menghasilkan sarjana, tetapi juga harus melatih mahasiswa menjadi problem solver yang bisa menavigasi kompleksitas dunia nyata. Salah satu cara yang sangat mungkin dilakukan adalah mengubah orientasi tugas akhir dan capstone project. Jangan lagi hanya menjadikannya sebagai syarat administratif untuk kelulusan, tapi posisikan sebagai proses kreatif untuk menghasilkan solusi nyata. Bayangkan jika setiap mahasiswa teknik menyelesaikan studinya dengan menghasilkan prototipe alat pertanian sederhana, mesin pengolahan limbah rumah tangga, atau aplikasi monitoring sistem irigasi desa. Inovasi-inovasi ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa jika diadopsi oleh masyarakat. Bukan hanya menyelesaikan masalah lokal, tapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Dengan pola pikir dan pendekatan semacam ini, mahasiswa tidak hanya belajar teknik, tetapi juga belajar memahami realitas sosial dan ekonomi yang akan mereka hadapi setelah lulus. Mereka akan terbiasa mencari solusi, bukan hanya mengerjakan soal. Mereka akan terdorong untuk menciptakan, bukan hanya menunggu. Dan perlahan tapi pasti, kampus akan mulai memetakan ulang perannya: bukan hanya mencetak lulusan, tapi juga mencetak pembaharu.
Saatnya Keluar dari Zona Nyaman
Saya percaya, ini saatnya kampus berhenti sibuk hanya pada urusan administratif seperti akreditasi dan peringkat. Hal-hal tersebut penting, tetapi bukan tujuan utama. Kampus harus mulai keluar dari zona nyaman dan hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat. Jangan hanya berdiri sebagai menara gading yang tinggi dan elitis, tapi jadilah jembatan antara ilmu dan kehidupan. Masyarakat tidak sedang menunggu kita lulus dengan gelar sarjana, magister, atau doktor. Mereka tidak menunggu judul penelitian kita yang rumit. Mereka menunggu solusi nyata. Mereka butuh teknologi yang bisa menyederhanakan hidup, gagasan yang bisa menghidupkan ekonomi lokal, dan inovasi yang bisa menyelamatkan lingkungan.
Bergerak Bersama, Berdampak Nyata
Transformasi menuju Kampus Berdampak bukanlah tugas satu atau dua orang. Ini tanggung jawab kolektif. Dibutuhkan keberanian dari para dosen, dukungan dari institusi, dan keberdayaan mahasiswa untuk bersama-sama bergerak. Pendidikan yang baik bukan hanya soal nilai dan kelulusan, tapi sejauh mana ilmu yang ditanamkan mampu menyuburkan kehidupan di luar tembok kampus. Jika kita serius, kampus bisa menjadi kekuatan transformatif. Tidak hanya mencetak lulusan, tapi juga menciptakan peradaban yang lebih baik.